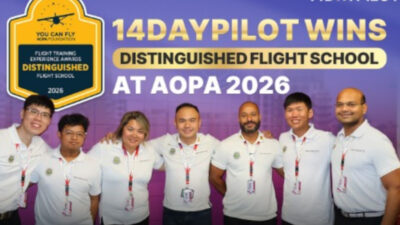TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pesantren telah lama menjadi benteng moral, sosial, dan spiritual bangsa Indonesia. Ia bukan hanya lembaga pendidikan agama, melainkan juga wadah pembentukan solidaritas sosial dan budaya yang kuat.
Dalam konteks sosial, pesantren berfungsi sebagai ruang sosial hidup yang membentuk jaringan kepercayaan, gotong royong, serta rasa tanggung jawab kolektif di antara santri, kiai, dan masyarakat.
Di Madura, peran ini tampak jelas melalui pesantren-pesantren yang berkolaborasi dengan Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan. Studi dalam Jurnal Al-Ulum UIM (2024) berjudul “Klan Kepemimpinan Pesantren dan Paternalisme sebagai Modal Sosial untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Islam” menegaskan bahwa kepemimpinan kiai dan loyalitas santri menciptakan struktur sosial berbasis kepercayaan dan penghormatan. Nilai-nilai ini bukan hanya menjamin keberlanjutan pendidikan pesantren, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat sekitar.
Contoh serupa terjadi di Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang dengan modal sosial antar alumni dan masyarakat berhasil mengembangkan koperasi dan BMT MMU hingga mencapai jaringan nasional.
Di Madura, pesantren seperti Maktab Nubdzatul Bayan Al-Majidiyah yang dibina oleh UIM juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan wirausaha dan pengelolaan wakaf produktif.
Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa pesantren adalah ruang produksi nilai sosial dan moral yang berperan langsung dalam memperkuat struktur sosial masyarakat Indonesia.
Konsep kapital sosial (social capital) menurut Robert D. Putnam (1993) mencakup tiga komponen utama: trust (kepercayaan), network (jaringan sosial), dan norms (norma sosial). Ketiganya tumbuh subur di lingkungan pesantren. Hidup berasrama, taat terhadap adab, dan interaksi antarsantri menciptakan ikatan sosial yang kuat dan solidaritas berkelanjutan.
Sementara Pierre Bourdieu (1986) memandang modal sosial sebagai sumber daya kolektif yang dapat dikonversi menjadi kekuatan sosial atau ekonomi. Dalam konteks pesantren, hubungan antara kiai, santri, dan alumni membentuk jaringan sosial yang berdaya guna. Hubungan ini bukan hanya spiritual, tetapi juga fungsional memunculkan kolaborasi ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Temuan UIM Pamekasan (2023) memperkuat teori tersebut. Dalam risetnya, UIM menunjukkan bahwa paternalisme pesantren di Madura bersifat positif karena mengandung unsur kekeluargaan dan keteladanan, bukan dominasi. Struktur sosial yang hierarkis namun harmonis ini menjadi ciri khas modal sosial pesantren di Madura.
Pesantren juga berfungsi sebagai cultural broker, sebagaimana teori modal budaya (cultural capital) menjelaskan. Ia menjadi penjaga nilai-nilai lokal dari tradisi tahlilan, gotong royong, hingga dakwah berbasis budaya. Dengan demikian, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga penjaga moralitas dan peradaban bangsa.
Terkait hal ini terdapat fakta pro dan kontra di masyarakat. Kalangan yang pro mereka mengajukan beberapa alasan. Pertama, Pemberdayaan ekonomi berbasis sosial. Pesantren seperti Sidogiri dan Darussalam Blokagung berhasil memanfaatkan kepercayaan dan jaringan alumni untuk membangun koperasi, BMT, dan unit usaha produktif.
Kedua, Pembinaan karakter dan moral bangsa. Pesantren menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan toleransi, menjadikannya agen pembentuk karakter nasional.
Ketiga, Kolaborasi akademik. Universitas Islam Madura (UIM) melalui program pengabdian masyarakat LPPM menjalin kerja sama dengan pesantren untuk meningkatkan manajemen pendidikan dan ekonomi berbasis keislaman di Madura.
Keempat, Kemandirian finansial. Pesantren modern seperti Daarut Tauhiid Bandung memanfaatkan wakaf produktif untuk kegiatan sosial dan pendidikan (BWI, 2025).
Sementara itu dari pihak yang kontra juga memiliki beberapa alasan yang patut dipertimbangkan. Pertama, Keterbatasan fasilitas dan SDM. Pesantren kecil sering kekurangan sarana modern dan pendanaan tetap.
Kedua, Dualisme kurikulum. Sebagian pesantren masih terjebak antara mempertahankan sistem klasik dan mengikuti kurikulum nasional.
Ketiga, Stigma konservatif. Beberapa pesantren dicap kurang terbuka terhadap inovasi, meskipun kenyataannya banyak yang adaptif. Keempat, Ketergantungan pada donatur. Pesantren yang belum mandiri finansial masih bergantung pada bantuan eksternal.
Meskipun menghadapi tantangan, pesantren tetap memainkan peran strategis dalam membangun kapital sosial yang menjadi fondasi peradaban bangsa. Implementasi kapital sosial di pesantren tampak nyata dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi.
Beberapa aksi nyata yang telah dilakukan di antaranya adalah, pertama, Pesantren Ramah Lingkungan (PPIM UIN Jakarta, 2025). Dari 55 pesantren di 12 provinsi, 87% berhasil menjalankan program lingkungan berkelanjutan seperti pengelolaan sampah, konservasi air, dan pertanian organik.
Kedua, Pesantren Mitra UIM Madura (2023–2024). Melalui LPPM, UIM menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren yang mencakup pelatihan kewirausahaan santri, manajemen keuangan syariah, dan pengelolaan wakaf produktif.
Contoh suksesnya adalah Maktab Nubdzatul Bayan Al-Majidiyah Pamekasan, yang mampu meningkatkan ekonomi lokal dengan berbasis nilai spiritualitas dan gotong royong.
Ketiga, Pesantren Sidogiri Pasuruan misalnya, membangun koperasi pesantren dan jaringan ekonomi umat yang memperlihatkan bagaimana kepercayaan sosial dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi nyata.
Implementasi ini membuktikan bahwa pesantren bukan hanya lembaga spiritual, tetapi juga agen perubahan sosial-ekonomi yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Pesantren adalah fondasi kapital sosial dan peradaban bangsa Indonesia. Melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan nilai moral, pesantren mampu memperkuat kohesi masyarakat.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UIM Madura menunjukkan bahwa pesantren terus berevolusi menjadi pusat pembentukan karakter, ekonomi, dan peradaban bangsa.
***
*) Oleh : M. As’ad Ulil Abshor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |